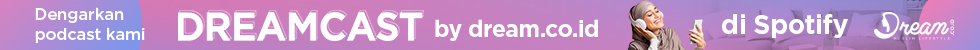|
| Ilustrasi |
Ada kalanya sebuah panggung politik kecil jauh lebih bising daripada gedung parlemen. Di sebuah gampong entah berantah, drama perebutan kursi kepala desa lebih heboh ketimbang rapat paripurna. Ironisnya, para aktor bukanlah politisi kelas nasional, melainkan warga yang mendadak merasa dirinya juru selamat demokrasi.
Dengan dada membusung, seorang warga tampil di depan media, menuding PJ Keuchik sebagai dalang segala kegaduhan. Katanya, sang PJ terlalu jauh mencampuri urusan pemilihan, sampai-sampai menagih syarat ijazah sekolah dasar yang tak ada dalam aturan. Tudingan itu disiarkan ke publik, lengkap dengan bumbu heroisme palsu, seolah ia baru saja membongkar skandal megakorupsi. Padahal, yang dipertontonkan hanyalah kebodohan telanjang: menyerang tanpa data, melolong tanpa bukti.
Dalam dunia satwa, serigala melolong untuk menunjukkan wilayah. Di gampong ini, orang melolong di media demi menunjukkan ambisi. Bedanya, lolongan serigala menimbulkan takut; lolongan politik lokal hanya menimbulkan tawa getir.
Lebih lucu lagi, tuduhan terhadap PJ dipoles dengan bumbu lama: soal bantuan rumah, soal gaji perangkat, soal transparansi dana. Semua dikemas bak arsip kejahatan besar, padahal sebagian besar terjadi sebelum PJ menjabat. Ibarat menuduh sopir baru yang menggantikan bus mogok, lalu menyalahkannya atas mesin rusak sejak lama. Di panggung ironi ini, logika pun dikubur dengan sukarela.
PJ dan perangkat desa, yang seharusnya bekerja dalam sunyi mengurus pembangunan, justru diposisikan sebagai kambing hitam permanen. Setiap gangguan aliran listrik desa, setiap sengketa batas tanah, setiap aroma busuk di selokan—semua bisa diarahkan ke meja PJ. Rasanya, hanya gempa bumi saja yang belum dituduhkan.
Yang lebih getir: tuduhan itu bukan sekadar salah alamat, tapi juga dipublikasikan dengan penuh kebanggaan. Seperti orang kampung yang menemukan teropong, lalu merasa bisa melihat seluruh jagat raya, padahal ia sedang menatap lubang kunci pintu.
Panggung politik desa memang kerap melahirkan tokoh-tokoh dengan telinga panjang tapi akal pendek. Mereka rajin mendengar bisikan, tetapi malas menimbang fakta. Rajin berkoar di media, tetapi lupa bahwa sejarah kecil gampong ini juga mencatat siapa yang dulu ikut menutup mata atas pelanggaran nyata.
Pada akhirnya, tudingan tanpa dasar hanyalah asap tanpa api: menyesakkan, membutakan, tapi mudah hilang ditiup angin. Dan seperti biasa, yang tersisa hanyalah wajah-wajah malu yang pura-pura tetap berwibawa.
(mis)