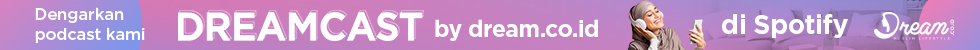|
| Ilustrasi |
Dua dekade lalu, negeri ini menorehkan sejarah: sebuah kesepakatan damai yang konon akan mengakhiri konflik panjang, menyatukan hati, dan menumbuhkan kesejahteraan. Mereka menyebutnya “MoU Helsinki.” Dua puluh tahun kemudian, kita diingatkan untuk merayakan damai—dengan diskusi internasional dan diplomat yang duduk rapi, menyeruput kopi sambil memuji keberhasilan.
Sementara itu, rakyat? Ah, rakyat tetap saja menatap jalan berlubang, sekolah roboh, dan lapangan kerja yang langka. Rupanya, MoU itu hebat—hebat untuk kalender acara pemerintah, tapi miskin hasil di lapangan. Sekitar 30–35% poin kesepakatan? Katanya belum terealisasi sepenuhnya. Tapi jangan khawatir, pejabat kita dengan sigap menepuk dada: “Damai sudah, cukup puas!”
Para mantan pejuang? Mereka tampak ikhlas, meski janji-janji yang dibuat di atas kertas tetap melayang entah ke mana. Ada yang menyebut ini “kesabaran rakyat,” ada pula yang menyebutnya “seni mengaburkan fakta.” Dan sementara eks kombatan menunggu program ketahanan pangan yang tak kunjung ada, pejabat sibuk menghadiri forum internasional, memberi pidato inspiratif tentang keberhasilan dan “tantangan yang harus dihadapi bersama.” Tantangan yang, ironisnya, sebagian besar berasal dari birokrasi sendiri.
Dana otonomi khusus? Hampir Rp96 triliun digelontorkan, katanya untuk pembangunan negeri. Tapi lihatlah kota dan desa: sebagian masih terjebak kemiskinan, sebagian lainnya menjadi saksi bisu ketimpangan pembangunan. Jalan-jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan proyek yang tertunda. Seolah pemerintah sedang bermain monopoli: lempar uang besar, lihat apa yang terjadi, dan tepuk tangan jika ada yang selamat dari kehancuran.
Yang paling lucu adalah ritual peringatan. Diskusi internasional, diplomat dari 12 negara, sesi refleksi—semuanya seperti panggung sandiwara. Semua orang tersenyum, menyatakan komitmen, dan menepuk punggung sendiri. Tapi ketika lampu padam dan para tamu pulang, janji-janji itu tetap terbaring di gudang arsip, sepi dan tak berguna.
Ah, negeri ini memang hebat: menciptakan “perdamaian” yang hanya terlihat dalam statistik dan publikasi media. Di permukaan, damai. Di bawah permukaan, janji tak ditepati, pembangunan melambat, dan rakyat tetap menelan pahitnya birokrasi yang lamban. MoU Helsinki? Lebih mirip mantra sakti yang membuat pemerintah terlihat rajin bekerja, sementara kenyataan di lapangan tetap sama: damai hanya untuk mereka yang duduk di kursi empuk, bukan untuk rakyat yang menunggu aksi nyata.
Tepuk tangan, para pejabat. Dua puluh tahun MoU, dua puluh tahun damai versi lembaran kertas. Sementara rakyat? Mereka masih menunggu—dengan sabar, atau mungkin dengan sinis, sambil menatap kalender ulang tahun peringatan yang sama setiap tahun.
(mis)