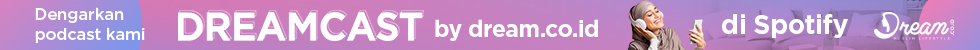|
| Ilustrasi |
Dua puluh tahun lalu, selembar kertas yang ditandatangani ribuan kilometer dari tanah konflik menjanjikan surga baru: peluru dimandulkan, darah disapu ke selokan sejarah, dan negeri ujung barat itu dijanjikan masa depan yang harum. Dua dekade berselang, yang harum justru bau jamuan hotel bintang lima, bukan nasi di meja rakyat jelata.
Para mantan jenderal, bekas panglima gerilya, politisi beruban, dan diplomat bersetelan necis kini berkumpul kembali di ruang berpendingin. Mereka saling menepuk bahu, berfoto dengan latar spanduk perdamaian, lalu menutup acara dengan secangkir kopi impor. Perdamaian, rupanya, lebih indah jika dipresentasikan dalam PowerPoint ketimbang diwujudkan di sawah dan ladang.
Konferensi ini disebut “refleksi.” Tapi, sejujurnya, siapa yang bercermin? Rakyat di pedalaman hanya punya cermin retak—hasil bantuan proyek yang mangkrak. Mereka yang berjubah penguasa punya kaca besar nan jernih, tapi lebih sering dipakai untuk merapikan dasi ketimbang menata nurani. Dua puluh tahun setelah senjata dikubur, yang tumbuh bukanlah sejahtera, melainkan istana-istana baru dari beton kekuasaan.
Kita diajak percaya bahwa perdamaian ini “inspirasi global.” Ironisnya, inspirasi itu berhenti di meja seminar. Dunia mungkin belajar cara menghentikan konflik, tapi tak ada modul tentang bagaimana menghentikan korupsi yang kini lebih subur daripada kopi Gayo. Senjata memang berhenti menyalak, tapi proyek-proyek anggaran menyalak lebih bising—membagi pundi-pundi seperti jarahan rampasan perang.
Dulu rakyat berdoa agar suara tembakan hilang dari malam. Kini mereka hanya ingin suara anak-anak mereka tidak hilang ditelan kemiskinan. Tetapi doa itu sering kalah oleh gemuruh tepuk tangan di auditorium. Perdamaian memang dijaga, tapi kesejahteraan dipinggirkan. Seperti pesta tanpa hidangan, hanya tuan rumah yang kenyang, tamu-tamu kecil pulang dengan perut keroncongan.
Dua dekade damai adalah prestasi. Tapi jika damai hanya jadi alasan untuk menggelar konferensi saban tahun, ia tak lebih dari kue ulang tahun yang habis disantap para elite, sementara lilinnya ditiup rakyat dengan napas yang makin pendek.
Perdamaian, sejatinya, bukan sekadar tidak ada perang. Ia seharusnya hadir di sawah yang terairi, sekolah yang tidak roboh, dan perut anak-anak yang tidak keroncongan. Sayangnya, dua puluh tahun ini, rakyat hanya diajak merayakan janji yang masih tertulis di kertas tua, sementara kenyataannya tetap disembunyikan di balik tirai seminar mewah.
(mis)