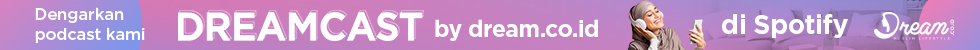|
| Ilustrasi |
Enam bulan terakhir, rakyat seperti dipaksa menonton sinetron dengan episode yang sama berulang-ulang: panggung megah, karpet merah, karangan bunga yang harganya bisa untuk memperbaiki satu jembatan desa, dan pita merah yang siap digunting demi kepuasan kamera. Pemain utamanya selalu sama—pemimpin berdiri gagah di podium, melafalkan naskah pidato penuh jargon yang sudah usang, lalu disambut tepuk tangan yang terdengar lebih seperti kewajiban daripada kebanggaan.
Setiap hari, jadwal pejabat penuh oleh seremoni. Peresmian kantor yang manfaatnya tak lebih dari hiasan gedung, ikut senam sehat sambil tertawa lebar di depan kamera, sementara di pelosok desa rakyat mengantri berobat di puskesmas yang bahkan tak punya obat. Ironisnya, di depan mata mereka, parkir liar yang merampas hak jalan umum dibiarkan begitu saja—mungkin karena tak ada pita merah untuk digunting di sana.
Jalan pertanian yang jadi nadi ekonomi rakyat dibiarkan jadi kubangan lumpur. Roda gerobak petani terkubur, tapi pejabat pura-pura buta. Mungkin bagi mereka, jalan yang layak hanya diperlukan menuju lokasi seremoni, bukan ke sawah atau pasar.
Lalu rakyat diminta bersyukur—katanya pembangunan sedang berjalan. Ya, pembangunan memang berjalan… di atas panggung seremoni. Sementara di dunia nyata, rakyat tetap terjebak di jalan berlubang, membayar beras yang makin mahal, dan minum air keruh karena pipa air bersih tak kunjung mengalir.
Bagi pemerintah, ukuran keberhasilan tampaknya bukan berapa banyak perut rakyat yang kenyang, tapi berapa banyak pita yang digunting dan foto yang diunggah ke media sosial. Sejarah tidak akan peduli berapa kali mereka tersenyum di depan kamera, tetapi akan mencatat betapa rajinnya mereka memotong pita sambil membiarkan kemiskinan tetap utuh.
Jika terus begini, rakyat akan menganggap panggung seremoni itu hanyalah drama simbolik yang hambar. Sebuah pertunjukan yang bahkan gratis pun tak layak ditonton—karena tiket masuknya dibayar dengan kesabaran rakyat yang makin menipis.
(mis)